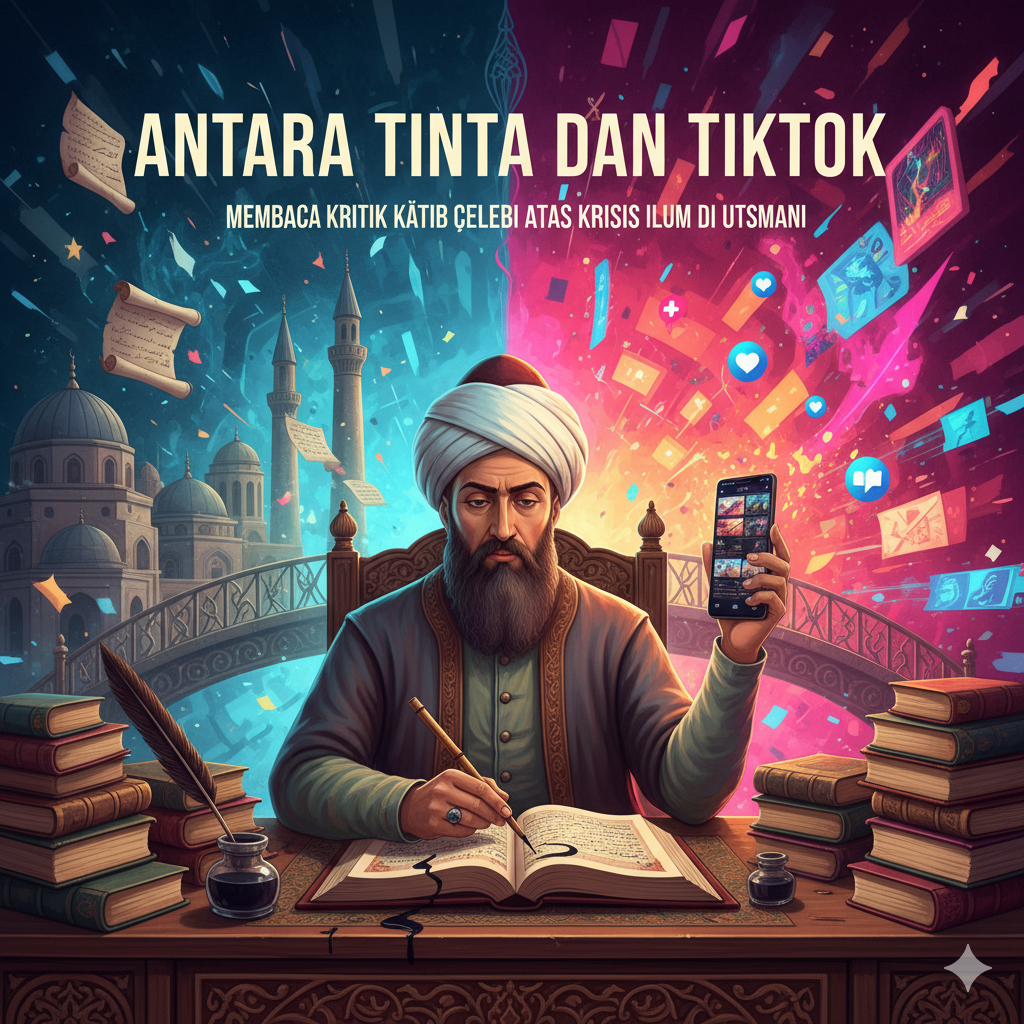Muhammad Luthfi
İlahiyat
İbrahim Çeçen Universitesi
Ketika masih duduk di bangku SMP, saya gemar membaca karya-karya Prof. Dr. Muhammad Ali Ash-Shalabi, seorang sejarawan dan guru besar dari Omdurman Islamic University, Sudan, yang dikenal luas melalui tulisan-tulisannya tentang dinasti-dinasti besar dalam sejarah Islam—dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, hingga Andalusia. Dalam setiap pengantar bukunya, beliau selalu menekankan satu prinsip mendasar: “Seorang sejarawan Muslim harus menguasai dasar-dasar hukum Islam sebelum meneliti sejarah.” (Ash-Shalabi, 2003, xii). Kalimat ini awalnya terasa normatif bagi saya, bahkan cenderung dogmatis. Namun, seiring bertambahnya usia dan perjumpaan saya dengan berbagai pemikiran di luar lingkaran intelektual saya sebelumnya, saya mulai memahami urgensi pernyataan tersebut—terutama ketika membahas isu-isu sensitif seperti representasi perempuan dalam sejarah Islam.
Sebelum menyelami lebih dalam tentang perdebatan ini, saya ingin menegaskan bahwa tulisan ini tidak bertujuan membahas seluruh spektrum epistemologi Islam atau tafsir gender dalam Islam secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah pada keterbatasan struktur naratif dalam historiografi klasik dan perlunya membaca sejarah Islam melalui kerangka syariah sebagai struktur epistemologis yang dominan dalam peradaban Islam. Maka dari itu, argumen dalam tulisan ini dibangun berdasarkan pendekatan fungsional-normatif, dan tidak mewakili seluruh perdebatan kontemporer tentang tafsir gender dalam Islam.
Sering kali kita terjebak dalam kerangka epistemologis Barat dalam membaca sejarah Islam, di mana narasi sejarah selalu diukur dengan visibilitas, partisipasi publik, dan kesetaraan dalam ruang sosial. Tak jarang muncul klaim bahwa perempuan dalam sejarah Islam didiskriminasi karena minimnya tokoh perempuan yang tercatat dalam literatur sejarah klasik. Sebagian kalangan feminis Muslim, seperti Leila Ahmed, berargumen bahwa narasi sejarah Islam secara struktural bersifat patriarkal dan mengandung bias gender yang melekat, baik dalam representasi tokoh perempuan maupun dalam konstruksi teologis yang mendasari masyarakat Islam. Dalam Women and Gender in Islam, Leila Ahmed menjelaskan bahwa sistem patriarki ini tidak hanya membatasi peran perempuan di ruang publik, tetapi juga membentuk wacana sejarah dan hukum Islam secara keseluruhan, sehingga narasi sejarah klasik cenderung mengabaikan atau meremehkan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang (Ahmed, 1992, p. 61-66).
Namun menurut saya, cara pandang ini justru mengabaikan struktur epistemologis yang membentuk sejarah Islam itu sendiri. Sebagaimana dicatat oleh Marshall Hodgson, Islam sebagai peradaban memiliki kesadaran sejarah yang kuat terhadap kesinambungan wahyu dan masyarakat, bukan sekadar narasi politik dan militer (Hodgson, 1974, p. 87-89).
Lebih jauh lagi, pandangan ini lahir dari pendekatan yang kurang menyeluruh terhadap sumber sejarah. Kita cenderung terlalu bergantung pada karya-karya naratif para sejarawan klasik yang mana sebagian besar karya sejarah klasik tersebut, seperti yang ditulis oleh al-Thabari, Ibn Katsir, atau Ibn al-Atsir memang bersifat elit-sentris (al-Ṭabarī, 2010, p.3-9) (Ibn Kathīr, 1994, p. 8-15). Mereka menulis untuk mendokumentasikan peristiwa besar: pergantian kekuasaan, penaklukan, pemberontakan, atau biografi para ulama ternama. Mereka menulis bukan untuk merekam kehidupan sehari-hari rakyat jelata, tetapi untuk mengabadikan peristiwa yang dianggap monumental. Inilah yang oleh para sejarawan kontemporer disebut sebagai great men historiography (Rosenthal, 1952, p.142-147) yang secara struktur naratif memang akan mengecualikan perempuan kecuali mereka masuk dalam arena elite kekuasaan. Maka tidak heran jika tokoh-tokoh perempuan jarang muncul dalam narasi mereka. Bukan karena mereka tidak penting, tapi karena genre penulisan sejarah saat itu memang berfokus pada ruang publik yang mayoritas diisi oleh laki-laki. Kita pun di era sekarang hanya mengunggah momen-momen besar dan membanggakannya ke media sosial, bukan rutinitas harian. Jadi, ketiadaan dalam teks bukan selalu berarti ketiadaan dalam realitas.
Namun sejarah tidak hanya disusun dari kitab-kitab besar. Ada juga sumber-sumber sejarah lain yang bersifat “diam”—apa yang disebut oleh para sejarawan sosial sebagai silent archives—tapi kaya makna: arsip fatwa, dokumen pengadilan, surat pribadi, manuskrip waqaf, hingga artefak arsitektur. Misalnya, dokumen pengadilan syariah di Damaskus, Istanbul, atau Kairo sering kali mencatat berbagai aspek kehidupan perempuan—dari perceraian, wakaf, hingga pengasuhan anak (Roded, 1994). Dalam konteks ini, perempuan tampil sebagai aktor sosial yang aktif dalam kehidupan publik, meskipun tidak selalu dalam ruang politik formal. Bahkan, ukiran nama perempuan pada bangunan masjid, madrasah, dan rumah sakit memperlihatkan keterlibatan mereka dalam amal jariyah dan proyek sosial keagamaan yang luas. Dari dokumen perceraian, kita memahami dinamika rumah tangga; dari catatan pribadi, kita mengenal pola pengasuhan; dari prasasti bangunan, kita melihat kiprah perempuan dalam filantropi. Di sinilah peran perempuan dalam masyarakat Islam mulai tampak lebih nyata dan menyeluruh—meski tidak selalu tercatat dalam narasi besar.
Namun pertanyaannya tetap: jika peran perempuan memang penting, mengapa mereka tetap jarang tampil sebagai tokoh sentral? Pertanyaan ini tidak selalu harus dijawab dengan kecurigaan terhadap diskriminasi struktural, tetapi juga dengan memahami bagaimana narasi sejarah Islam disusun. Di sinilah relevansi pernyataan Prof. Ash-Shalabi semakin terasa. Untuk memahami dinamika masyarakat Islam, kita tidak bisa menggunakan logika sekuler. Kita perlu memahami syariat sebagai kerangka utama yang membentuk relasi sosial dalam Islam, karena tanpa memahami syariat sebagai fondasi epistemologis masyarakat Islam, kita akan cenderung membaca sejarah dengan standar yang tidak selaras (Hallaq, 2009, p.202-207).
Dalam paradigma Islam, peran laki-laki dan perempuan tidak diposisikan secara identik, melainkan dibedakan secara fungsional. Bukan karena superioritas satu pihak atas yang lain, melainkan karena masing-masing diberikan tanggung jawab yang berbeda demi keharmonisan sosial. Laki-laki memikul tanggung jawab kepemimpinan—yang tidak hanya bermakna kuasa, tetapi juga beban dan amanah—sementara perempuan memiliki peran yang justru lebih mendasar dalam konstruksi sosial: mendidik generasi, menanamkan nilai, dan menjaga kesinambungan moral keluarga. Tanpa kontribusi perempuan dalam ranah domestik dan pendidikan anak-anak, masyarakat Muslim akan kehilangan fondasi yang menopang keberlangsungan warisan keislaman dari generasi ke generasi.
Selain itu, Islam tidak menyamakan ketenaran dengan kemuliaan. Popularitas bukan tolak ukur keutamaan. Islam tidak memuja popularitas, melainkan ketakwaan. Bahkan Rasulullah ﷺ menyandingkan air mata yang jatuh dalam shalat malam dengan darah yang tumpah di medan jihad. Ini menegaskan bahwa ukuran keutamaan bukan pada ruang tampil, tapi pada keikhlasan menjalankan peran yang ditentukan Allah. Maka, dominasi laki-laki dalam narasi sejarah klasik bukanlah indikator superioritas moral atau spiritual mereka, melainkan cerminan dari fokus naratif yang lebih menyoroti peristiwa eksternal seperti perang, kekuasaan, dan politik. Jika historiografi Islam terlihat maskulin, itu lebih merupakan hasil dari struktur dan gaya penulisan sejarah, bukan pernyataan nilai tentang siapa yang lebih utama dalam agama. Ini sekaligus menjadi kritik epistemologis terhadap anggapan bahwa hanya yang tampak di ruang publik yang layak dicatat sebagai sejarah.
Lalu bagaimana dengan perempuan yang memang tampil di ruang publik? Di sinilah pentingnya memperhatikan sejarah yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah Tarkan Khatun, istri Sultan Malikshah dari Dinasti Seljuk. Dalam Saljūqnāmeh, ia digambarkan sebagai penguasa de facto yang mengambil alih kekuasaan politik setelah suaminya wafat. Ia berhasil melobi Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadī bi-Amr Allāh secara pribadi di Baghdad untuk mengangkat putranya, Mahmud, sebagai penerus takhta, memerintahkan khutbah dibacakan atas namanya, dan mengangkat wazir serta panglima baru untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya. Saljūqnāmeh bahkan menyebut bahwa “Khatun mengirim pasukan untuk berperang dan mengepung Isfahan, ibukota Kekaisaran Seljuk Raya”—sebuah frasa yang mencerminkan otoritas militer yang ia kendalikan (An-Naysabūrī, 2010, p.115). Ia tidak hanya aktif dalam intrik politik istana, tetapi juga memobilisasi kekuatan militer untuk mempertahankan dinasti. Kita berbicara tentang seorang perempuan yang mampu memegang tampuk kekuasaan pada puncak politik Islam abad ke-11—di jantung kekhalifahan dan dunia Islam.
Namun penting untuk ditegaskan bahwa eksistensi tokoh seperti Tarkan Khatun adalah pengecualian, bukan norma yang harus diberlakukan kepada semua perempuan. Islam membuka ruang peran yang variatif bagi perempuan: dari ruang domestik hingga istana, dari madrasah hingga medan dakwah. Dalam Islam, keberartian seseorang tidak ditentukan oleh lokasi perannya, melainkan oleh nilai kontribusinya dalam menegakkan agama dan menjaga keseimbangan sosial. Maka, ketika perempuan tampil di ruang publik, hal itu bukan bentuk perlawanan terhadap norma syariah, melainkan ekspresi dari fleksibilitas peran dalam batas-batas yang digariskan wahyu.
Sebagaimana dikatakan Urwah bin Zubair, “Seandainya ilmu Aisyah binti Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan dan ilmu seluruh penduduk Madinah di sisi lain, maka ilmu Aisyah akan lebih berat.” (Al-Zarkashī, 1997, p.45). Ini bukan sekadar pujian terhadap kecerdasan Aisyah, tetapi pengakuan bahwa kontribusi perempuan dalam Islam sering kali terjadi dalam ruang-ruang yang tak kasat mata namun sangat menentukan arah peradaban. Seperti Aisyah yang tidak pernah membuka majelis ilmu, beliau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat senior dari balik tabir rumahnya.
Sejarah Islam, jika dibaca melalui kerangka epistemologis yang sesuai, justru menampilkan peran perempuan yang esensial namun sering kali tak tercatat dalam narasi-narasi dominan. Ini bukan karena perempuan dikesampingkan secara nilai, melainkan karena genre historiografi klasik lebih menekankan peristiwa eksternal dan struktur kekuasaan formal. Dalam hal ini, prinsip keadilan Islam tidak identik dengan penyamaan peran (musāwah), melainkan penempatan yang adil dan fungsional (ʿadl).
Keadilan dalam Islam bukan berarti semua orang harus hadir di tempat yang sama atau dalam peran yang identik, tetapi bahwa setiap individu diberikan ruang untuk berkontribusi secara optimal sesuai dengan maqām, kapasitas, dan konteksnya—semua dalam bingkai wahyu. Maka, membaca sejarah Islam tidak cukup hanya dengan menelusuri peristiwa dan nama-nama besar, tetapi juga memerlukan pembacaan struktural yang mempertimbangkan syariat sebagai kerangka normatif dalam pembentukan masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak berarti “semua tampil”, melainkan “semua terhitung”.
Bibliografi:
- An-Naysabūrī, Muḥammad ibn ʿAlī. Saljūqnāmah. Terjemah Aslı Özlem Tarakcıoğlu & Ayşe Gül Fidan. Gaithersburg: Kopernik, 2021.
- Ash-Shalabi, Muhammad Ali. Tārīkh al-Dawlah al-ʿUthmāniyyah. Kairo: Maktabah al-Aqṣā, 2003.
- Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven: Yale University Press, 1992.
- El-Rouayheb, Khaled. Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Hallaq, Wael B. Shari‘a: Theory, Practice, Transformations. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hodgson, Marshall G. S. The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Ibn Jarīr al-Ṭabarī. Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2010.
- Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar. Al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Rosenthal, Franz. A History of Muslim Historiography. Leiden: Brill, 1952.
- Roded, Ruth. Women in Islamic Biographical Collections: From Ibn Saʿd to Who’s Who. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1994.
- Al-Zarkashī, Muḥammad al-Muʿtaṣim Billāh al-Baghdādī. Al-Ijābah li Irād Mā Istadrakathu ʿĀ’ishah ʿalā al-Sahābah. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997.