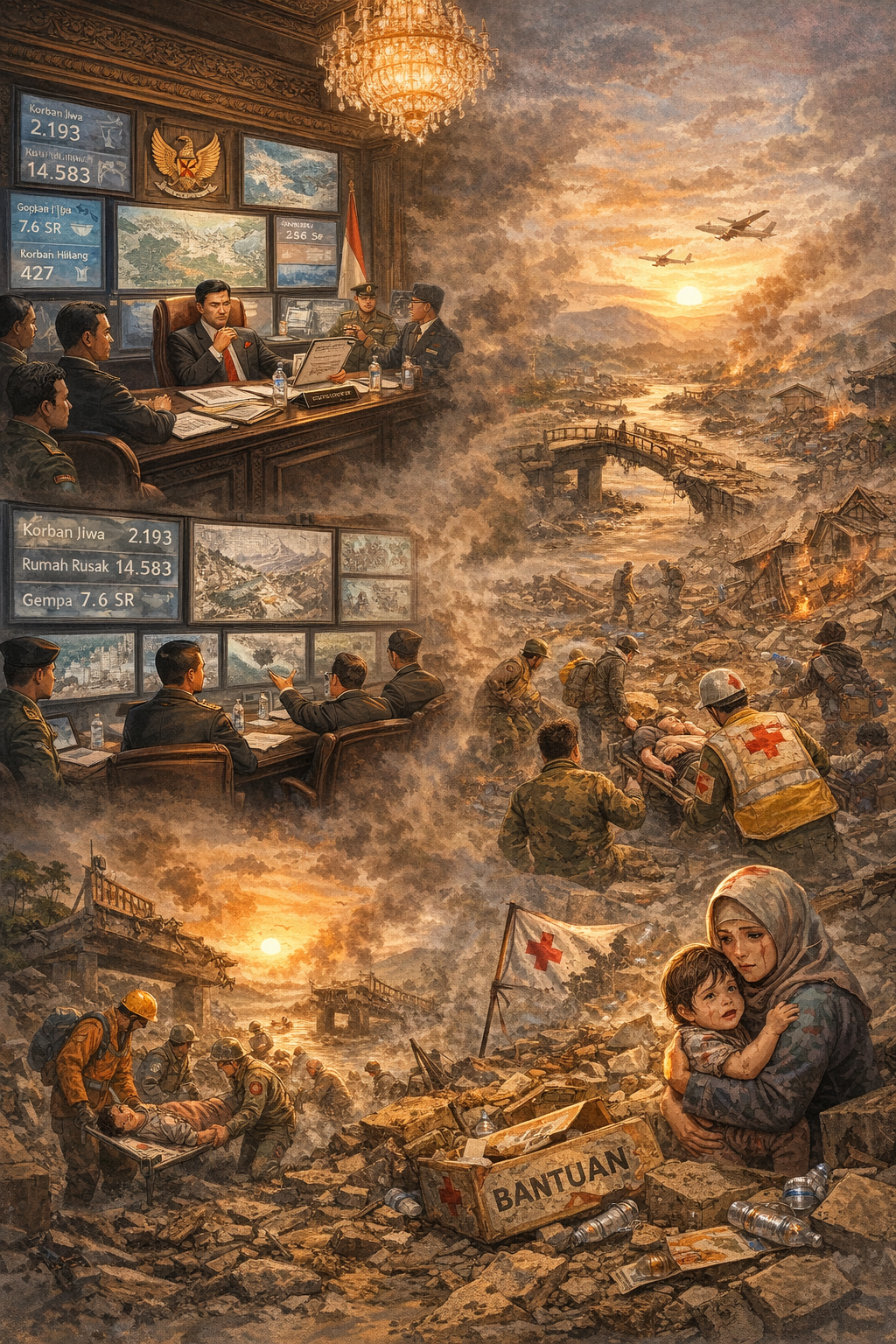Andi Aulia Khairunnisa
Maliye Yüksek Lisans (Public Finance)
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi
Setiap 21 April, kita mengikuti rutinitas nasional: mengenakan kebaya, mengutip “Habis Gelap Terbitlah Terang,” dan menggelar lomba bertema perempuan. Namun, di balik perayaan ini, ada ironi yang tak kunjung selesai: kita merayakan Kartini di atas struktur yang terus-menerus membungkam cita-citanya. Ia telah mati berkali-kali, bukan karena usia, tapi karena sistem yang enggan berubah. Dan tiap tahun, alih-alih membangkitkannya, kita justru memakamkannya ulang, dengan upacara yang semakin kosmetik.
Kartini hari ini tidak hadir di ruang-ruang kelas pelosok negeri, di mana anak perempuan harus memilih antara pendidikan atau membantu ekonomi keluarga. Ia tidak duduk di kursi birokrasi yang didominasi maskulinitas kebijakan. Ia tidak berjalan di lorong-lorong pabrik tempat perempuan dibayar lebih rendah, apalagi di ruang-ruang politik yang masih melihat tubuh perempuan sebagai alat elektabilitas, bukan subjek kebijakan.
Yang lebih menyakitkan, bahkan di jalanan pun Kartini tak merasa aman. Tubuh perempuan telah menjadi “ruang publik” yang bebas dikomentari, diraba, bahkan dilanggar. Negara lambat merespons, hukum sering kali tak berpihak, dan masyarakat justru membungkam perempuan dengan narasi-narasi moralitas yang bias gender. Ini bukan hanya kegagalan penegakan hukum, ini kegagalan kebijakan sosial, budaya, dan politik yang tidak berpihak kepada keamanan hidup perempuan.
Kita hidup dalam struktur negara yang secara formal mengafirmasi kesetaraan, tetapi secara praktik membiarkan ketimpangan mengakar. Masih banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki layanan kesehatan reproduksi yang layak bagi perempuan. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih terganjal oleh prosedur yang mempermalukan korban. Dan pendidikan, sektor yang begitu dijunjung oleh Kartini masih menjadi kemewahan bagi banyak perempuan di pinggiran republik.
Kartini adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi ironinya, kolonialisme kini hadir dalam wajah baru: sistem patriarki yang dilembagakan melalui budaya, ekonomi, dan bahkan hukum. Maka memperingati Kartini tanpa menggugat sistem adalah bentuk pengkhianatan terhadap warisan intelektualnya. Kartini tidak menginginkan seremoni, ia menuntut transformasi.
Memajukan perempuan bukanlah upaya estetika. Ia adalah kerja politik. Dan kerja ini harus dimulai dari pengakuan bahwa struktur yang kita hidupi hari ini masih memihak kepada dominasi laki-laki. Jika negara sungguh ingin mewujudkan keadilan gender, maka ia harus berani melakukan koreksi terhadap desain kebijakan publik yang selama ini netral secara teks, tetapi bias secara praksis.
Kartini bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah ide dan ide tidak mati, kecuali jika kita berhenti memperjuangkannya. Maka tugas kita hari ini bukan hanya mengenang, tetapi melanjutkan perlawanan. Bukan hanya membicarakan kesetaraan, tapi mengakarnya dalam kebijakan, anggaran, dan sistem pendidikan.
Dan selama struktur ini belum berpihak pada hidup perempuan, kita akan terus menyaksikan kematian Kartini dalam berbagai bentuk.