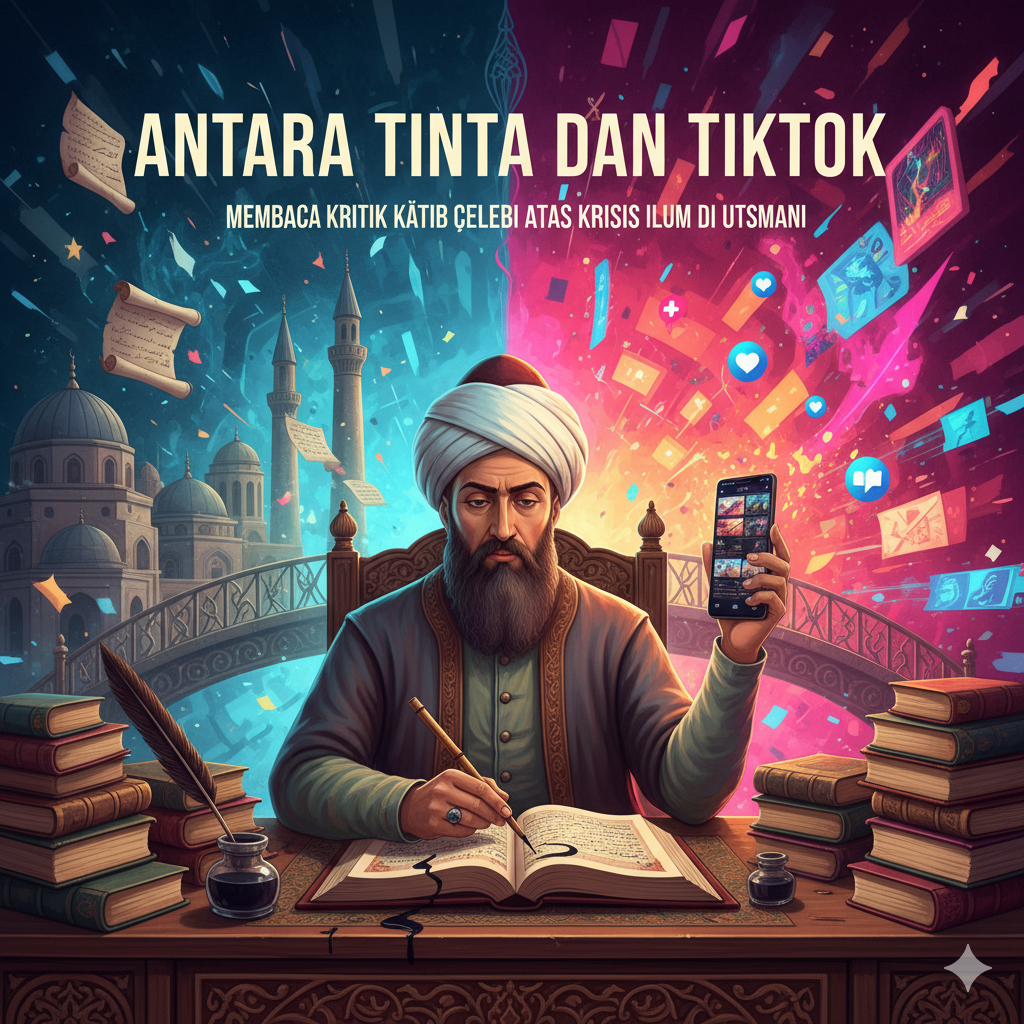Muhammad Luthfi
İlahiyat
İbrahim Çeçen Universitesi
Memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025 rasanya bukan sekadar seremonial, melainkan momen refleksi besar-besaran bagi seluruh santri di Indonesia. Peristiwa demi peristiwa yang menimpa dunia pesantren akhir-akhir ini memaksa kita untuk menengok kembali nilai-nilai, subkultur, dan praktik keseharian yang selama ini kita jalani. Dalam hati kecil, kita sesungguhnya menyadari bahwa setiap tindakan santri, dari cara berpakaian hingga cara berpikir, memiliki landasan epistemologis dan tradisi keilmuan yang panjang, terlepas dari mazhab mana yang menjadi pegangan. Namun, bagi masyarakat luas, penjelasan-penjelasan ilmiah itu seringkali tidak relevan. Mereka tidak menuntut uraian fikih atau dalil-dalil usuliyyah; yang mereka butuhkan hanyalah kejelasan moral, transparansi komunikasi, dan ketegasan sikap dari para penjaga ilmu agama atas berbagai tragedi yang terjadi di tengah mereka.
Sebagai seorang santri, saya sepenuhnya menyadari betapa luas dan mengakarnya khazanah keilmuan Islam. Ia bukan sekadar kumpulan doktrin, melainkan sebuah bangunan epistemologis yang terbentuk selama ribuan tahun oleh para ulama lintas zaman dan tempat, yang bekerja dengan disiplin, kecermatan, dan ketulusan intelektual. Karena itu, tidak mungkin bagi kita untuk secara sepihak meruntuhkan warisan keilmuan yang telah disusun sedemikian sistematis oleh para pendahulu. Melakukan hal itu sama saja dengan meragukan kapasitas dan keagungan intelektual mereka—para penjaga warisan ilmu yang tingkatannya jauh melampaui kita. Maka, apa yang saya maksud di sini bukanlah perombakan, melainkan evaluasi: evaluasi terhadap diri kita sebagai santri, terutama dalam hal bagaimana cara kita mengomunikasikan ilmu syariah yang begitu luas dan dalam ini kepada masyarakat umum, agar mereka dapat memahaminya dengan mudah, tanpa merasa terintimidasi oleh bahasa keilmuan yang kita gunakan.
Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kita hidup di abad ke-21, tepatnya di dekade 2020-an—sebuah era di mana batas antara dunia nyata dan dunia maya nyaris menghilang. Internet bukan lagi sekadar medium, melainkan ruang hidup yang sesungguhnya. Dunia digital kini menjadi locus utama interaksi, transaksi, dan bahkan pembentukan identitas. Artinya, apa yang dahulu disebut “maya” kini justru menjadi “nyata,” sementara dunia fisik yang kita tempati perlahan berubah menjadi semacam latar fiksi—ruang jeda tempat kita sekadar memenuhi kebutuhan biologis seperti makan, mandi, dan tidur.
Dalam ruang ini, globalisasi mencapai bentuknya yang paling ekstrem: bukan hanya bangsa yang saling berinteraksi, tetapi juga kelas sosial yang sebelumnya tak pernah bersinggungan kini saling melihat dan berkomentar secara langsung. Kita menyaksikan bagaimana seorang rich crazy Surabaya melakukan food challenge di TikTok, seorang banker ternama membagikan edukasi finansial di IG Reels, dan akademisi senior membuka kanal YouTube untuk mengajar tanpa bayaran. Semua ini menunjukkan bahwa batas-batas ekonomi, profesi, dan otoritas telah mencair dalam satu medium besar bernama internet. Dan dari sisi dunia santri, artinya masyarakat umum—bahkan mereka yang mungkin belum pernah sekalipun menyentuh mushaf al-Qur’an—bisa melihat, menilai, bahkan beropini tentang kehidupan pesantren melalui potongan video, unggahan singkat, dan komentar spontan.
Pesantren, yang dahulu merupakan ruang tertutup dan hening—tempat adab dipelajari perlahan bersama ilmu—kini menjadi panggung yang bisa disorot oleh siapa saja. Dunia yang dahulu dijaga oleh batas waktu dan tata krama kini tampil berdampingan dengan segala hal yang banal, lucu, bahkan profan. Perubahan ini, suka tidak suka, adalah konsekuensi dari keterbukaan zaman. Seorang santri yang sedang menulis catatan fiqh atau membaca kitab ushul seringkali tampil di layar publik bersamaan dengan konten ringan, humor, atau bahkan kegaduhan sehari-hari. Di sinilah titik refleksi penting: dunia maya telah menggeser batas antara yang sakral dan yang profan, antara yang formal dan yang kasual, dan menuntut kita untuk menemukan cara komunikasi yang jujur, mudah dipahami, sekaligus tetap menjaga integritas ilmu.
Pengalaman ini mengingatkan saya pada fenomena yang pernah terjadi di akhir Daulah Utsmaniyah, ketika keseimbangan antara otoritas formal Şeyhülislam, otoritas moral dan sosial tarekat, dan kekuasaan Sultan mulai mengalami tekanan internal. Kâtib Çelebi, salah seorang intelektual besar Utsmaniyah, menyoroti bahwa ʿulamaʾ kerap menjadi “ahl al-jadal”—lebih sibuk dalam perselisihan hukum dan akademik daripada membimbing masyarakat secara moral. Kritik Çelebi bukan sekadar menyoroti perilaku individu, tetapi menunjukkan dampak struktural dari birokratisasi, patronase, dan pewarisan jabatan terhadap legitimasi sosial ulama. Di banyak kota seperti Aleppo, Baghdad, dan Konya, qadi dan mufti sibuk mengurus administrasi medrese, membangun reputasi di Istanbul, dan mengelola jaringan patronase, sementara persoalan nyata masyarakat—sengketa pertanian, konflik antar-kampung, kebutuhan spiritual sehari-hari—sering terabaikan.
Dalam kerangka Weberian, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep routinization of charisma. Pada awalnya, Şeyhülislam bukanlah pejabat negara; ia adalah figur moral dan karismatik, mampu menyeimbangkan dan menjembatani kepentingan Sultan dengan tuntutan masyarakat. Karisma personal ini membangun legitimasi moral yang kuat. Namun, ketika posisi ini menjadi birokratis, dapat diperjualbelikan, atau diwariskan (tevliyet), karisma personal mulai tergerus oleh formalitas institusional. Jabatan turun-temurun memang menunjang stabilitas, tetapi mengikis kemampuan pemimpin untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan memengaruhi moral ummat. Fenomena serupa terjadi pada tarekat-tarekat Sufi: shaykh yang awalnya memimpin dengan karisma personal dan kedekatan spiritual dengan murid, lama-kelamaan harus menyesuaikan diri dengan struktur formal, birokrasi wakaf, dan hierarki lembaga. Legitimasi moralnya tersalurkan melalui prosedur institusional, sementara keakraban spiritual dengan murid dan masyarakat mulai menipis.
Menyadari paralel ini membuat saya—seorang santri abad ke-21—merenung tentang posisi kita dalam dunia digital. Sama seperti ʿulama dan shaykh Utsmaniyah yang terjebak antara birokrasi dan karisma, santri modern juga menghadapi dilema antara tradisi keilmuan dan tuntutan transparansi publik. Ketika video membaca kitab, ceramah, atau doa beredar di media sosial, masyarakat menilai bukan dari kedalaman ilmiah kita, tetapi dari kedekatan moral dan otentisitas kita sebagai individu. Seorang santri yang mampu menegakkan adab, membimbing teman, dan mempraktikkan ilmu dalam keseharian, akan lebih diapresiasi daripada sekadar mengutip dalil panjang lebar yang tidak dapat dipahami oleh khalayak umum.
Oleh karena itu, dunia pesantren harus belajar dari sejarah. Seperti halnya masyarakat Utsmaniyah yang mencari figur alternatif ketika ulama kehilangan legitimasi karena terlalu sibuk dengan birokrasi, masyarakat digital sekarang menilai santri berdasarkan pengaruh moral dan sosial yang nyata, bukan hanya gelar atau jabatan resmi. Seorang santri yang aktif dalam aktivitas sosial, membantu tetangga, atau menyelenggarakan kajian sederhana yang dapat diikuti siapa saja, secara tidak langsung meniru logika legitimasi moral tarekat yang tetap relevan meski mulai memiliki struktur formal.
Pengamatan ini membawa kita pada pemahaman mendalam: pendidikan agama bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter dan bimbingan moral. Kita dapat belajar dari kritik Çelebi bahwa keberhasilan otoritas agama ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara birokrasi formal dan karisma moral. Birokrasi memberi stabilitas, tetapi karisma moral membangun kepercayaan dan kedekatan. Santri kontemporer harus mampu menyeimbangkan keduanya, terutama ketika berinteraksi dengan dunia digital yang transparan, cepat, dan sering kali menuntut jawaban singkat tetapi bermakna.
Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang santri yang rutin membaca Al-Qur’an di pondok. Jika kegiatannya hanya menjadi rutinitas internal—dicatat di buku harian, diulang-ulang tanpa pemahaman, tanpa refleksi, tanpa komunikasi—maka nilai moral dan spiritualnya terbatas pada lingkungan terbatas itu. Namun, ketika santri tersebut mulai membagikan renungan singkat di Instagram, menjelaskan makna ayat secara sederhana, atau menampilkan praktik adab sehari-hari dalam video, ia mengekspresikan karisma moralnya secara lebih luas. Interaksi ini, meskipun terbatas dan terpotong-potong, meniru logika tarekat yang tetap relevan melalui kedekatan sosial, sambil mempertahankan legitimasi formal melalui pemahaman ilmu yang benar.
Fenomena ini menegaskan bahwa santri modern hidup dalam “tekke digital”: sebuah ruang di mana otoritas moral dan sosial diuji secara terbuka. Tidak cukup sekadar menghafal kitab atau menegakkan disiplin internal pondok. Dunia maya menuntut transparansi, relevansi, dan komunikasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara tradisi keilmuan dan kebutuhan moral masyarakat. Dalam kerangka Weber, ini adalah bentuk baru routinization of charisma: karisma tidak hanya dipraktikkan melalui bimbingan personal, tetapi juga melalui manajemen reputasi digital, keterlibatan sosial, dan pengaruh moral yang dapat dirasakan oleh publik luas.
Lebih jauh, pengalaman kontemporer ini menegaskan pelajaran dari sejarah Utsmaniyah: birokratisasi tanpa karisma moral menimbulkan jarak antara institusi dan masyarakat. Santri modern yang hanya menekankan prestasi akademik, hafalan kitab, atau formalitas adat pondok, tanpa menunjukkan kepedulian moral nyata, akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat yang sekarang mengakses dunia melalui layar. Sebaliknya, santri yang tetap mempertahankan integritas, kesabaran, dan bimbingan moral, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, akan tetap dihormati dan dipercaya, persis seperti shaykh di tekke yang karismatik dan responsif terhadap kebutuhan murid dan masyarakatnya.
Dengan demikian, Hari Santri 2025 bukan hanya momentum perayaan, melainkan ajakan refleksi: bagaimana kita, sebagai generasi penerus pesantren, dapat menyeimbangkan tradisi keilmuan, karisma moral, dan tuntutan dunia digital. Kita belajar dari sejarah: dari kritik Çelebi terhadap ulama birokratis, dari transformasi Şeyhülislam dan tarekat, dan dari konsep Weber tentang routinization of charisma. Kita menyadari bahwa legitimasi moral dan kedekatan sosial adalah fondasi yang tidak bisa diabaikan, bahkan di tengah arus informasi yang deras dan dunia maya yang penuh distraksi.
Seorang santri yang mampu menjaga keseimbangan ini—antara disiplin ilmu, kedekatan moral, dan kemampuan berkomunikasi dengan dunia luar—adalah santri yang tidak hanya menegakkan tradisi, tetapi juga menjadikannya relevan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan pesantren tidak diukur hanya dari kedalaman kitab atau ketepatan adab, tetapi juga dari kemampuan menyalurkan karisma moral dan legitimasi sosial ke ranah yang lebih luas, termasuk dunia maya yang kini menjadi bagian dari ruang hidup kita sehari-hari.